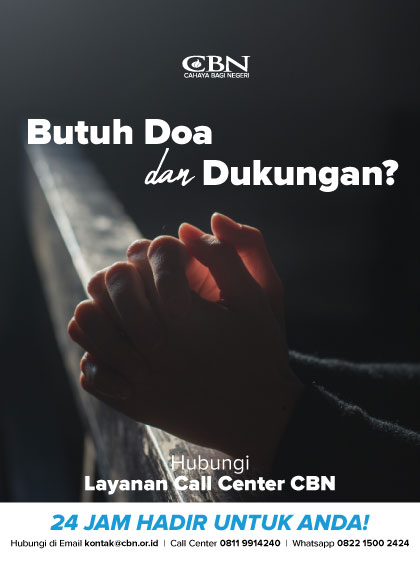Parenting / 1 May 2011
Apakah Kebahagiaan Sejati Itu?

Lestari99 Official Writer
Saya masih ingat kunjungan-kunjungan ke rumah nenek saya waktu masih kecil. Saya biasa tidur di kamarnya yang mungil, di tempat tidur yang dialasi seprai berbau harum. Di meja makannya selalu tersedia makan kesukaan saya yang mengundang selera. Nasi yang saya makan di rumah nenek selalu lebih enak dari nasi yang ada di rumah kami.
Penampilan nenek saya juga selalu memukau. Dengan rambut yang terisir rapi dan senantiasa dicat hitam setiap kali mulai memutih. Pakaian model terbaru yang membungkus tubuhnya yang ramping pantas membuat iri para anak muda. Dan tentunya bau semerbak dari parfumnya selalu menarik saya untuk selalu dekat dengan tubuhnya.
Bukan cuman hal-hal fisik itu saja yang membuat saya kagum, tapi sikapnya yang selalu bersukacita dan mengucap syukur, seakan-akan telah terjadi mujizat setiap hari. Dalam bayangan kanak-kanak saya, nenek saya adalah seorang yang kaya dan berkecukupan.
Setelah beranjak remaja (atau mungkin dewasa, saya lupa tepatnya), barulah saya menyadari bahwa nenek saya adalah seorang janda miskin - ini kalau dibandingkan dengan orang-orang di lingkungannya.
Mengapa saya tidak pernah menyadari kenyataan itu waktu saya masih kecil?
Mata kanak-kanak saya yang masih polos dan belum dipengaruhi oleh prinsip-prinsip materialisme dan konsumerisme sama sekali tidak bisa membedakan ukuran kaya dan miskin dari sudut materi. Bagi saya, orang yang berbahagia adalah orang yang kaya.
Tidak lagi sekarang, setelah lingkungan memaksa saya untuk mengerti tentang prinsip ekonomi. Apalagi setelah lulus dari fakultas ekonomi, seluruh pelajaran yang saya ingat selama empat tahun berkuliah dapat disimpulkan dalam satu kalimat: “Kepuasan manusia tidak ada batasnya”.
Saya membaca majalah dan melihat betapa cantik serta tampannya para model yang sedang memperagakan pakaian bermerk. Tidak heran waktu remaja, saya hanya ingin memakai baju yang bermerk ke sekolah. Rasanya ketinggalan kalau di badan kita tidak menempel merk yang dikenal orang.
Saya menonton TV yang menayangkan sinetron dimana para bintangnya tinggal di rumah megah dan mengendarai mobil mewah. Meskipun selalu ada gadis yang miskin dan kurang beruntung namun pada akhirnya seorang pangeran kaya raya akan mempersunting dirinya untuk menjadi permaisuri. Cerita ala Cinderela ini telah begitu merasuk banyak gadis muda yang menghayalkan tentang pangeran imipian yang menikahinya, tinggal di sebuah istana megah dan hidup bahagia selama-lamanya.
Saya pergi ke gereja dan juga menerima pengajaran bahwa Tuhan menginginkan semua manusia hidup kaya dan sehat senantiasa. Ditambahkan lagi, bahwa pada prinsipnya semakin banyak kita memberi maka akan semakin banyak berkat yang akan kita terima. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi dermawan dengan harapan pemberian mereka menjadi investasi yang akan memberikan keuntungan melimpah.
Tanpa disadari, bahwa pandangan kanak-kanak saya yang polos tentang arti kebahagiaan itu telah berevolusi. Disinilah awal mula saya memandang nenek saya sebagai janda malang yang tidak memiliki apa-apa. Saya mulai mengingini apa yang juga dikejar oleh mayoritas manusia di muka bumi: uang! Ada salah kaprah besar yang mengganti paradigma saya selama ini: materi = kebahagiaan.
Saya merasa tertipu karena ternyata paradigma itu menyesatkan. Uang, harta benda, materi bukanlah sumber kepuasan. Kekayaan bukan alasan untuk menjadi lebih bahagia. Tanyakan itu pada anak-anak yang belum dikotori oleh agama materialisme itu, mereka tidak memiliki apa-apa namun mereka adalah makhluk yang paling bersukacita di muka bumi ini. Mereka melompat gembira untuk sepotong permen dan tertawa senang ketika diberi kesempatan untuk bermain lumpur di luar rumah. Mereka berbahagia hanya oleh hal-hal yang sederhana dan berterima kasih untuk hal yang kita anggap sepele. Saya sering bangga ketika anak saya berkata “Thank you Mummy” setelah dibuatkan segelas susu coklat, yang kemudian akan dilanjutnya dengan “I love you Mummy, so much!”
Perlu waktu bertahun-tahun untuk mengisi kepolosan pandangan kanak-kanak saya dengan paham materialisme dan saat ini perlu waktu yang panjang pula untuk membersihkan pikiran saya dari apa yang telah saya terima dari dunia tersebut.
Namun, saya bersyukur sebagai wanita biasa, akhirnya sadar sebelum terlambat. Bukan di rumah penantian atau di tempat tidur kematian, hikmat itu datang. Tidak perlu ada penyesalan karena pengertian tentang kehidupan datang menerpa. Saat ini apa yang terpenting bagi saya adalah mengejar sesuatu yang lebih berharga dari harta benda, dialah HIKMAT. Amsal berkata, “Karena hikmat lebih berharga dari pada permata, apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya”.
Saya juga bersyukur karena mengenal sumber dari hikmat tersebut dan hidup di dalamnya sejak waktu saya masih sangat muda. “Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan”. Takut akan Tuhan ini yang telah menghindarkan saya dari banyak malapetaka yang akan membuat penyesalan seumur hidup. Takut akan Tuhan yang telah menyadarkan saya dari kebodohan-kebodahan yang membelenggu. Hikmat yang timbul darinya akhirnya mengembalikan kita pada kenyataan, pada esensi kehidupan. Hidup sesuai dengan rancangan Ilahi, menurut saya itulah kebahagiaan sejati.
Penulis adalah seorang konselor profesional dan juga penulis buku "Turning Hurt Into Hope" (Metanoia 2009).
Sumber : Nancy Dinar