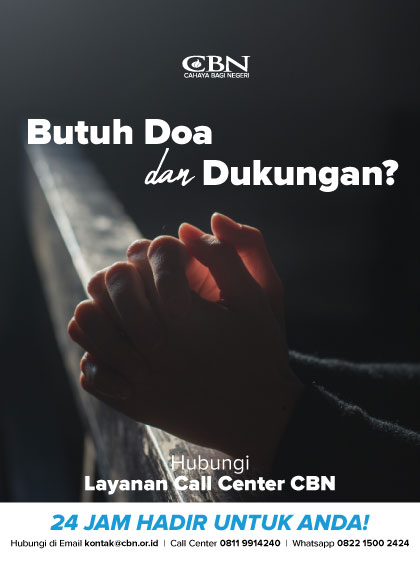Nasional / 17 August 2009
Reflection of Wong Jowo

Lestari99 Official Writer
"Saiki jaman edhan, yen ora edhan ora kedhuman" (sekarang ini zaman edan, kalau tidak ikut edan, tidak akan mendapat tempat atau bagian). Demikianlah kita sering dicekoki dengan semboyan tersebut. Sebagai orang Jawa, atau lebih tepat seseorang yang tumbuh di lingkungan dengan nilai-nilai Jawa yang cukup kental, hal ini sangat mengganggu saya. Semboyan ini banyak sekali mempengaruhi generasi ini.
Sungguh benar sekali dugaan saya hukum Vilfredo Parreto 20/80 hanya berlaku untuk nilai-nilai yang positif, sementara untuk nilai-nilai yang negatif maka perbandingannya adalah 80/20. Dimana saat 100 nilai-nilai baik ditanamkan, yang diserap dengan baik hanya oleh 20% audiens saja. Sedangkan saat nilai nilai negatif ditanamkan maka akan dengan mudah diserap dan diterima adalah oleh 80% audiens. Manusia memiliki kecenderungan untuk lebih mudah menerima hal-hal negatif ketimbang nilai positif.
Sungguh menyesakkan bagi kita, sebenarnya begitu banyak nilai-nilai positif dari budaya Jawa yang dilupakan begitu saja. Sekarang nasehat-nasehat tersebut hanya didapat dari Dalang Wayang, yang sudah tergusur oleh kesenian dangdut dan organ tunggal. Bahkan pertunjukkan Wayang yang diadakan semalam suntuk banyak ditinggal tidur saat ngudhal piwulang (memaparkan ilmu dan hikmat). Sementara negara tetangga sangat antusias untuk mengklaim banyak dari hasil budaya kita.
Selain semboyan "Jaman Edan" itu sebenarnya sangat banyak nilai dan norma yang dimiliki oleh Budaya Jawa. "Mo-Limo" contohnya, dijabarkan sebagai maling (mencuri, termasuk juga korupsi), madat (nyabu dan narkoba), main (berjudi), minum (mabuk-mabukan), dan madon (main perempuan). Semuanya sebagai pantangan, yang harus dijauhi (prefentif), diberantas (post facto), dan pihak-pihak yang jadi korban diobati (kuratif). Namun banyak sekali dilakukan oleh anak muda generasi kita.
 Seorang pria Jawa hanya bisa disebut memiliki hidup yang sempurna bila memiliki 5 hal, yaitu: curigo, wismo, turonggo, kukilo, garwo. Curigo adalah keris, merupakan perumpamaan dari penghasilan atau mata pencaharian. Wismo adalah rumah. Turonggo adalah kuda, merupakan perumpamaan dari kendaraan. Kukilo adalah burung berkicau, merupakan perumpamaan dari hobi. Garwo merupakan kependekan dari sigaran jiwo yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah separuh jiwa, dengan kata lain isteri. Sungguh sangat bertolak belakang dengan apa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dimana semua orang ngoyo (memaksakan diri) untuk berkeluarga sebelum memiliki kehidupan yang layak. Keluarga miskin sangat banyak jumlahnya akibat dari pernikahan tanpa tanggung jawab.
Seorang pria Jawa hanya bisa disebut memiliki hidup yang sempurna bila memiliki 5 hal, yaitu: curigo, wismo, turonggo, kukilo, garwo. Curigo adalah keris, merupakan perumpamaan dari penghasilan atau mata pencaharian. Wismo adalah rumah. Turonggo adalah kuda, merupakan perumpamaan dari kendaraan. Kukilo adalah burung berkicau, merupakan perumpamaan dari hobi. Garwo merupakan kependekan dari sigaran jiwo yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah separuh jiwa, dengan kata lain isteri. Sungguh sangat bertolak belakang dengan apa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dimana semua orang ngoyo (memaksakan diri) untuk berkeluarga sebelum memiliki kehidupan yang layak. Keluarga miskin sangat banyak jumlahnya akibat dari pernikahan tanpa tanggung jawab.
Seorang pemimpin Jawa hanya dapat disebut berhasil bila: Ing ngarso suntulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Ing ngarso suntulodo artinya bisa menjadi teladan saat di depan. Sayangnya banyak pemimpin kita justru Ing ngarso sontoloyo, sebelum jadi pemimpin saja kita sudah tahu betapa sontoloyo akhlak dan budi pekertinya. Ing madya mangun karso artinya di tengah ikut serta atau dengan kata lain, bisa mengkaryakan diri, ikut mengambil tanggung jawab, memiliki andil dan partisipasi yang nyata. Justru yang kita temui adalah Ing madya mbalelo atau di tengah seenaknya sendiri, egois, selalu ingin diutamakan. Tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan, selalu memotivasi dengan tulus, tanpa perlu muncul di atas panggung, tidak mencari keuntungan sendiri. Kita malah temukan, tut wuri medheni atau di belakang mengerikan, mengkritik tidak pada tempatnya, suka menjatuhkan, menjelek-jelekkan orang lain.
Sangat disayangkan pula, bangsa ini sudah sangat terpesona dengan semboyan "witing tresno jalaran soko kulino" (cinta itu datangnya karena terbiasa). Padahal yang tidak biasa itu kadang-kadang adalah yang lebih baik dan lebih tepat. Kita dituntut nrimo (menerima) dengan membiasakan diri dengan apa yang sebenarnya tidak membangun kita, kita dituntut untuk menerima apa yang sebenarnya bukan yang terbaik untuk kita. Semboyan tadi dijadikan alasan untuk tidak memberi pilihan untuk berpikir. Semboyan itu mengeliminasi pilihan-pilihan kita, kita dijejali pilihan yang tidak kita sukai dengan harapan kita menjadi terbiasa, lalu mencintai pilihan itu. Padahal pilihan itu hanya menuai penyesalan di kemudian hari.
Dan sungguh sangat bodoh bila kita menilai pilihan berdasar agresifitas promosi, karena dalam subyektifitas semua menjadi kabur dan tidak jelas. Kita sering kehilangan obyektifitas hanya karena kita terbiasa dengan pola lama. Kita menghindari perubahan dan hidup nrimo dalam status quo.
Akhir kata, bangsa ini hanya akan menjadi bangsa yang maju bila menghargai estetika budayanya. Dan tidak hanya menghargainya tetapi juga mempraktekkan apa yang baik dan positif untuk perubahan. Pembangunan mental dan karakterlah penentu perubahan. Siapakah saya? Saya hanya rakyat jelata yang terus mencari hikmat seorang brahmana, mencoba hidup dengan nilai-nilai satria, berusaha sebagai seorang waisya, dan tetap merendahkan diri sebagai seorang sudra. Seorang yang tergelitik melihat kejadian sehari-hari dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Terima kasih untuk Ki Dalang di kampung sana yang sudah memberi banyak wejangan. Salam untuk perubahan, majulah Indonesiaku.
God bless! Merdekaaa!
Sumber : Cahyadi Tanujaya