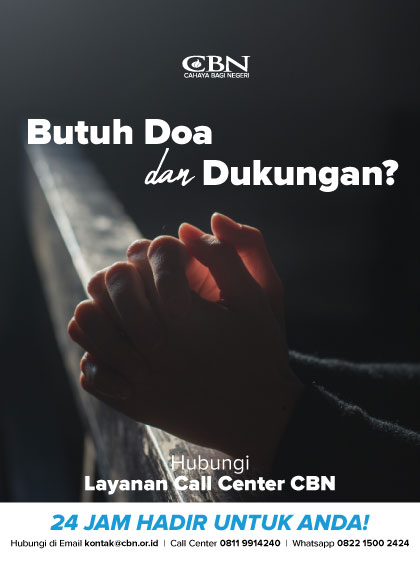Parenting / 22 November 2010
Menjadi Orangtua Yang Positif

Lestari99 Official Writer
Setiap kali akan pergi ke suatu acara, kerusuhan selalu terjadi di rumah saya. Emosi seringkali terlontar ketika harus mempersiapkan anak-anak untuk pergi. Berkejaran dengan waktu, kami berusaha keras untuk tidak saling menyakiti satu sama lain.
Selama bertahun-tahun dengan anak-anak yang bertumbuh semakin besar, peperangan ini pun sedikit mereda. Tetapi putri terkecil saya yang baru berusia 9 tahun seringkali menjadi penghambat utama terciptanya perdamaian dan selalu membuat kami semua nyaris terlambat. Namun ajaibnya, dalam sebuah kesempatan ia muncul di depan pintu kamar saya, sudah berpakaian dan siap pergi untuk tidak membuat kami terlambat. Tapi sayangnya rambutnya masih sangat berantakan. Respon saya tidak terlalu antusias saat itu.
“Lihat rambutmu Molly! Kamu tidak bisa keluar rumah seperti itu!” teriak saya. “Berapa kali Mama harus bilang untuk menyisir rambutmu?”
Namun saya segera menyesali respon itu ketika saya melihat ekspresi wajahnya yang menunjukkan kehancuran hati.
“Saya sudah berusaha keras pagi ini, Ma,” ujarnya pelan. “Tidak bisakah saya mendapatkan sedikit pujian?”
Sifat perfeksionis saya langsung tersentak. Saya secara alami cenderung untuk mengkritik daripada bersikap positif. Dan seringkali saya berusaha keras untuk tidak terbawa dengan emosi. Sayangnya, menjadi seorang anak di rumah saya ternyata menjadi sesuatu yang sulit.
Namun syukurlah beberapa tahun yang lalu, Tuhan mulai membuka mata saya untuk melihat bagaimana kritikan saya justru menghancurkan semangat anak-anak saya dan secara perlahan semakin menjauh dari ikatan kami sebagai orangtua dan anak. Tuhan mendorong saya untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada diri saya yang akhirnya memberi pencerahan.
Apakah Saya Menginginkan Hubungan Atau Segala Sesuatu Harus Berjalan Dengan Benar?
Seringkali saya memang cukup benar tentang banyaknya kekurangan yang anak-anak saya miliki. Namun yang perlu digaris-bawahi adalah: Kritik yang dilakukan terus-menerus dapat menghalangi keintiman. Kekeras-kepalaan saya selalu memandang bahwa saya benar. Padahal akan lebih baik bagi saya untuk mencoba memilih dengan hati-hati pertengkaran saya, untuk menciptakan lingkungan rumah yang penuh keterbukaan, rahmat dan kasih sayang.
Apakah sebagai orangtua kita pernah lebih benar dari Yesus sendiri? Bahkan Yesus tidak pernah menjalankan kekuasaan-Nya dengan kapak pertempuran. Koreksi yang disampaikannya sangat instruktif, tidak merusak, memberikan kebijaksanaan praktis untuk membantu mencegah terulangnya kesalahan di masa mendatang.
Yohanes 8 menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang berzinah dan bagaimana orang-orang Farisi berusaha melemparinya dengan batu sebagai hukuman atas dosa-dosanya. Yesus, bagaimanapun juga, tidak menghukum atau mengkritik perempuan berdosa itu. Yesus tidak mencaci maki atau meneriakkan kejahatan yang telah dilakukannya. Sebaliknya, Yesus menawarkan kasih dan anugerah, sambil memberikan instruksi yang jelas (“Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.” Yohanes 8:11) dan memberikan kesempatan kedua kepada wanita itu untuk melakukan kebenaran.
Apakah Ini Tentang Karakter Atau Kontrol?
Sebagaimana pertumbuhan saya sebagai orangtua, saya menyadari seringkali saya tergoda untuk mengkritik karena itu menyangkut preferensi saya. Saya menjadi frustrasi karena anak saya tidak melakukan sesuatu seperti yang saya mau.
Saya pun mulai bertanya pada diri saya sendiri, “Apakah ini benar-benar penting? Apakah ini menyangkut masalah karakter mereka yang perlu saya perhatikan atau masalah kontrol yang perlu saya abaikan? Apakah ini tentang mereka atau tentang saya?”
Berbohong dan bersikap tidak hormat misalnya, menjadi keharusan untuk melakukan pendisiplinan yang efektif. Namun ketika itu menyangklut lemari pakaian atau tempat tidur yang berantakan juga bisa melemahkan ikatan di antara orangtua dan anak ketika kita menempatkannya sebagai masalah utama.
Apakah Tujuan Saya Kinerja Atau Gairah?
Orang-orang Farisi merupakan pengikut aturan yang sejati dari hukum Taurat. Namun Yesus justru membandingkan mereka dengan “kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran.” (Matius 23:27)
Semangat untuk mengkritik memang dapat menyebabkan kepatuhan secara lahiriah, tetapi juga melahirkan kebencian yang laten, sikap menghakimi terhadap orang lain, dan nilai-nilai yang berakar pada kinerja. Seperti para ahli Farisi, anak-anak kita menjadi ahli untuk mencari keburukan-keburukan orang lain terlebih dahulu.
Yang paling penting untuk diingat adalah terus mengkritik kesalahan secara negatif dapat berdampak pada persepsi anak-anak terhadap Tuhan. Mereka belajar untuk melihat Tuhan sebagai Allah yang suka menghukum, bukan penuh dengan kasih karunia. Daripada mempercayai Tuhan mereka lebih memilih untuk kuatir. “Saya tidak pernah bisa memenuhi standar orangtua saya. Bagaimana bisa saya menjadi cukup baik untuk Tuhan?”
Ketika kita meneladani kasih dan anugerah-Nya, kita akan mengarahkan anak-anak kita kepada Bapa yang pemaaf, sabar dan menerima kita apa adanya. Ketaatan kemudian mengalir dari hubungan tersebut, bukan karena takut ataupun karena penyerangan secara verbal.
Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. – Amsal 16:23-25
Kita tidak bisa terikat dalam hubungan jika tidak memberikan pengaruh. Kita bisa saja membiarkan emosi keluar dari mulut kita, meluncurkan kata-kata yang dapat melukai anak-anak kita secara permanen. Atau, perkataan-perkataan kita dapat menjadi perkataan yang positif dan membangun, mendorong anak-anak kita untuk terus bertumbuh dalam kasih. Pilihan ada di tangan Anda.
Sumber : Melinda Means - cbn.com