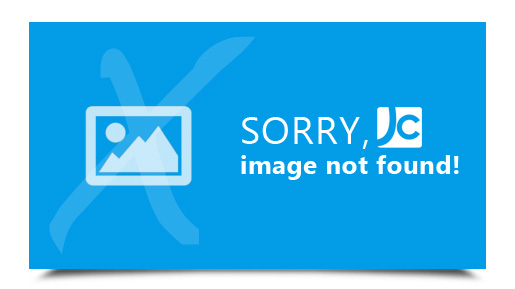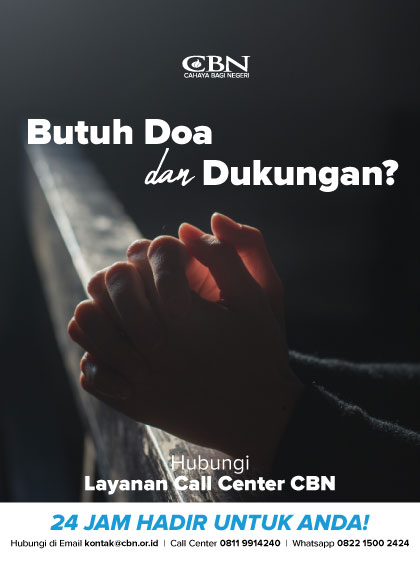Entrepreneurship / 16 August 2010
Anak Tuhan Dalam Kemerdekaan RI

Lestari99 Official Writer
Tahi Bonar Simatupang (1920-1990) yang biasa dipanggil Pak Sim ini lahir di tengah keluarga dengan tradisi gereja Lutheran yang saleh. Anak kedua dari tujuh bersaudara ini besar dengan adat Batak yang kuat. Ayahnya, Simon Mangaraja Soaduan Simatupang, terakhir bekerja sebagai pegawai PTT.
Pak Sim betah untuk berlama-lama membaca atau menulis sesuatu. Ia tidak pernah lepas dari kaca mata. Istrinya, Sumarti Budiardjo, kebetulan adalah adik teman seperjuangannya, Ali Budiardjo. Pak Sim dan Bu Sumarti sudah mulai akrab sewaktu berlangsung Konferensi Meja Bundar. Bersama dengan Bu Sumarti, mereka memiliki empat orang anak, namun sayang salah seorang anaknya meninggal dunia.
Di masa kemerdekaan, Pak Sim sempat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang RI. Laporan dari Banaran adalah salah satu renungan yang ditulisnya tentang serangan mendadak Belanda atas Yogya di pagi hari tanggal 19 Desember 1948. “Saya tengah rebahan di dipan dan belum melepas pakaian, ketika menjelang matahari terbit terdengar suara pesawat berdesingan di udara. Saya menoleh ke atas dari jendela, saya lihat pesawat terbang dengan tanda-tanda Belanda. Ngayogyakarta Hadiningrat, ibu kota Republik pujaan kita, telah diserang,” tutur Pak Sim.
“Apakah pagi ini lonceng matinya Republik sedang dibunyikan? Atau apakah Republik kita akan lulus dalam ujian ini?” Pada saat yang sama, pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab sendiri oleh Pak Sim. “Itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita yang menyebut diri kaum Republiken, hari ujian bagi kita telah tiba. Apakah kita hanya sebatas loyang (ember dari kaleng) atau emas?”
Pagi itu tanpa mandi atau cuci muka sekalipun, Pak Sim dengan sigap menghubungi kawan-kawan seperjuangannya untuk menentukan langkah. Keadaan memang gawat. Yogya jatuh ke tangan belanda. Presiden, Wakil Presiden dan para pemimpin lainnya telah ditawan Belanda. Seperti pajurit-prajurit yang lain, Pak Sim kemudian bergerilya.
Padahal beberapa hari sebelumnya Pak Sim masih sibuk sebagai Penasehat Militer Delegasi RI dalam perundingan-perundingan yang menghasilkan Perjanjian Renville dan lantas aktif pula dalam perundingan lanjutannya di Kaliurang, 24 kilometer di utara Yogya. Namun semua hasil perundingan itu batal dengan serangan Belanda ke Yogya pagi itu.
Sebagai seorang diplomat, hari itu secara reflek Pak Sim mengenakan ‘seragam’ yang khusus ia kenakan selama mengikuti perundingan dengan pihak Belanda, di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara. Setelan celana abu-abu dan kemeja buatan luar negeri itulah yang melekat di badannya selama beberapa minggu bergerilya. Akibat pakaiannya inilah ia sering diolok-olok sebagai ‘diplomat kesasar’.
Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang RI (1948-1949) dan Kepala Staf Angkatan Perang RI (1950-1954) pensiun dini tahun 1959 dengan pangkat Letnan Jenderal.
“Saya pensiun oleh karena tidak dapat lagi bekerja sama dengan Presiden Soekarno,” ujar Pak Sim dalam bukunya Iman Kristen dan pancasila (BPK Gunung Mulia, 1984).
Pensiun bukan berarti saatnya beristirahat bagi Pak Sim. Ia terus aktif dalam lembaga pendidikan (sempat menjadi Ketua yayasan dan pembinaan manajemen) dan dalam organisasi keagamaan. Pak Sim menjalani kehidupan reflektif di DGI (Dewan Gereja-Gereja Di Indonesia) yang sekarang bernama PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia).
“Di DGI, mungkin saya akan bisa memberikan sumbangan yang kecil dalam pengembangan landasan-landasan etik teologi bagi tanggung jawab Kristen di suatu masa,” tutur Pak Sim.
Jenderal yang selalu merasa berutang ini tenggelam dalam kesibukannya sebagai aktivis gereja. Pak Sim kemudian menjadi Ketua Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (1959-1984), Ketua Dewan Gereja-Gereja se-Asia dan Ketua Dewan Gereja-Gereja se-Dunia.
Th. Sumartana selaku intelektual muda dari kalangan Kristen menyebut Pak Sim sebagai “Teoretikus oikumenis pertama yang lahir dari lingkungan gereja-gereja di Indonesia setelah kemerdekaan.”
Pak Sim adalah salah satu bukti sejarah nyatanya andil anak Tuhan dalam perang kemerdekaan RI. Menyambut Ulang Tahun RI, marilah setiap pihak melakukan perenungan yang mendalam akan perjuangan para pahlawan kita di zaman dulu dari setiap lapisan dan golongan tanpa memandang latar belakang agama dan suku mampu bersatu-padu berjuang bagi kemerdekaan negeri ini.
Sumber : tokohindonesia